Bola Mata di Ruang Redaksi
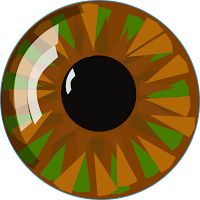 |
| Ilustrasi from google |
Sejak
pertemuan singkat itu, aku tak lagi melihatmu. Hingga suatu ketika, kasus
mading membawaku kembali menatap kamu. Bahkan lebih lama.
“Mading
apaan ini? Jelek banget sih?” aku bergumam miring di depan papan berkaca yang
ada di lorong sekolah itu. Tanpa aku sadari, seseorang menguping celotehanku.
“Kalau
jelek, perbaiki dong! Jangan hanya bisa ngomong!” sindirmu. Aku gelagapan
bingung. Saat itu, aku tahu persis kalau kamu pimred di sekolah yang megah ini.
Aku hanya tersenyum. Senyum yang malu-maluin. Dan semenjak itu, aku dan kamu
adalah partner yang baik untuk
menghidupkan mading itu. Bahkan, kamu tak segan-segan memilihku sebagai ketua
mading.
Masih
ku ingat aksi pertama kita. Di sore yang gerimis, aku, kamu dan teman-teman
seperjuangan berjubelan di dalam ruang redaksi. Tujuannya, buat perenovasian
mading tentunya. Entah mengapa, liukan tanganku melembut, tutur kataku melemah.
Untuk pertama kali, rasa itu muncul. Di ruang redaksi, untuk pertama kalinya
aku benar-benar ada bersamamu.
Tak
disangka, ruang redaksi kembali menyeret kita berdua untuk masuk ke sana. Pagi
itu, hanya ada aku dan kamu di sana. Hanya kita! Peristiwa itu masih melekat di
memoriku. Lelaki sopan itu memintaku untuk membersihkan ruang redaksi. Jaket
coklat yang membungkus badanmu bergumpalan debu. Hidungmu mengeluarkan cairan
yang menggelikan. Hingga matamu memerah, dan wajahmu memucat.
“Kamu
kenapa? Sakit?” tanyaku khawatir.
Kamu
menggeleng. Aku kembali memastikanmu “Are
you okay?” aku menatap matamu lekat-lekat. Mata yang bulat, lebar, dan
tajam. Kamu pasti kelelahan. Batinku bersimpati.
“Nggak
papa kok. Tenang aja!” jawabmu lembut. Suaramu berat. Aku yakin kamu sakit.
Tapi, sebagai lelaki tangguh, pantang bagimu mengumbar rasa sakitmu.
Belakangan, baru aku ketahui kalau kamu alergi debu.
Sore
yang diguyur hujan, seorang lelaki memojokkan kita. Yah, dia pembina kita.
Kesalahan berita yang aku tulis dan aku tempelkan di mading membuatku tak
bergerak. Payahnya, aku dan kamu disidang bersama. Aku hanya menopangkan tangan
di atas meja. Menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Ruang redaksi itu serasa
menyempit. Saat ku angkat kepalaku, tanpa rencana, mata kita kembali beradu.
Dengan seulas senyum yang kau pasang di sana. Aku kebingungan mengartikan
senyum itu. senyum kasihankah, atau senyum kebahagiaankah.
Di
sore yang berbeda, dengan hujan yang berbeda. Di ruang redaksi yang masih sama.
Aku kembali mendapati binaran matamu. Tapi, kali ini penuh dengan cinta.
“Aku
ingin menembak dia. Bagaimana menurutmu?” tamumu sambil menunjukkan foto
seorang gadis cantik padaku. Aku melemas. Tak ada jawaban. Aku mencari pegangan
jika sewaktu-waktu tubuhku tumbang. Kemudian aku tersenyum sambil menganggukkan
kepala. Hatiku yang tadi mendesir damai, kini berkecamuk tak karuan. Dan kamu
benar-benar menembak dambaan hatimu itu.
Selepas
sore itu, aku tak berani lagi mendatangi ruang redaksi. Karena bagiku, ruangan
itu terlalu panas dan memilukan untuk ku diami. Karena tanpa ku sadari, hatiku
telah tertambat di sana. Di hatimu. Dan berakhir kandas di ruang redaksi.
Hingga
suatu sore di ujung tahun akademi, kamu memaksaku kembali ke sana. Kau
benar-benar mentap mataku lekat. Sangat dalam dan penuh makna. Aku tak berani
mengangkat kepalaku. Bagiku, memandangmu adalah sebuah kesalahan.
“Aku
akan kuliah di Australia. Tiga hari lagi aku berangkat.” Kini, tubuhku
melumpuh. Pamitmu padaku sore itu benar-benar menggoreskan luka yang
berdarah-darah.
Aku
hanya bisa berkata “Doaku menyertaimu.” Aku tak mungkin membuntutimu hingga ke
sana. Kewajiban sekolahku masih tinggal setahun lagi. Dan aku benar-benar tak
berminat untuk berkelana jauh. Meski di hati aku belum siap melepasmu, tapi aku
kembali menimbang. Siapa aku? Aku tak berhak mencegah niat baikmu. Lama sekali
perbincangan kita di ruang redaksi sore itu. dan kau buka semua tentangmu
padaku.
“Aku
sudah putus satu minggu yang lalu.”
“Hah?
Putus? Kenapa?” tanggapku memastikan kalau aku tak salah dengar.
Kamu
menggeleng. “Karena dia nggak jago nulis kayak Kamu!” jawabmu sambil tersenyum
lebar. Aku tahu itu hanya candaanmu. Kalau kamu mencari yang sepertiku, kau
pacaran saja denganku. Ternyata, kau bisa bercanda juga. Aku pikir, kau hanya
bisa serius dua rius.
“Aku
pulang dulu ya!” katamu sambil beranjak. Aku mengikutimu.
“Kalau sudah di Australia, jangan lupa kabari aku ya!” oh tuhan, mengapa serasa berat sekali melepasmu?
“Kalau sudah di Australia, jangan lupa kabari aku ya!” oh tuhan, mengapa serasa berat sekali melepasmu?
Kamu
mengangguk. “Nggak usah kangen aku ya!” celetukmu sambil mengelus kepalaku. “Aku
pasti akan merindukanmu! Jangan berhenti untuk belajar nulis. Dan jangan takut
bermimpi.” Ohhh.... aku terbang melayang sore itu!
Bagaimana
aku tidak merindukanmu? Ku beranikan diri menatap bola matamu lebih lama. Di
sanalah ku simpan kristalku yang paling berharga. Ku resapi setiap nyalanya.
Tak berkedip sedikitpun, kau juga menatapku. Yang tanpa ku duga, itu adalah
bola mata terakhirmu yang bisa kulihat. Sebulan sebelum kamu pergi untuk
selamanya.
Sidorejo, 3 Januari 2014
*Alay banget nih cerpen.. Tapi gpp lah.. mohon dimaklumi ya, dulu waktu aku bikin ini masih labil.. sekarang? Sekarang tambah labil! :D



Comments
Post a Comment